You are currently browsing the category archive for the ‘Adat & Budaya’ category.
Oleh Yusradi Usman Al-Gayoni *
Abdul Latif, demikianlah nama salah seorang pengarang, sekaligus ceh pada kelop (kelompok/grup Didong) Kebinet, Bebesen, Takengon, Aceh. Kelop ini terbilang kelop tua dalam dunia didong di tanoh Gayo. Didong sendiri merupakan seni yang memadukan puisi, gerak, dan vokal. Tanggal 21 November 2009, kebetulan penulis bertemu Abdul Latif, yang kerap disapa Atif, di salah tempat pangkas rambut di Kampung Simpang Pet, Kecamatan Bebesen, Takengon. Bagi masyarakat Bebesen dan Takengon, Latif merupakan salah satu ceh kul (ceh legendaries, dan cukup disegani). Penulis kerap mendengar namanya dari masyarakat. Namun, belum pernah bertemu, dan bercerita secara khusus soal didong, dan keterlibatannya di dalamnya.
Karenanya, kesempatan yang jarang terjadi tersebut, penulis manfaatkan untuk menanyakan soal keterlibatannya dalam, dan umumnya soal didong. Tatapan kosong Atif tertuju pada antrian mobil yang ada di bawah. Kami sendiri; penulis, awan (kakek) Dahlan, dan ama (bapak) Atif berada di tempat yang lebih tinggi. Tepatnya, di tempat pangkasnya awan Dahlan. Gerimis hujan, menjadikan tempat tadi bertambah dingin, terlebih-lebih saat angin dari arah kampung Bebesen berhembus. Memang, saat itu, dan sejak penulis berada di Takengon, hampir setiap hari, kota Takengon terus diguyur hujan. Dengan penuh penjiwaan, keluar-lah suara yang kurang terdengar begitu jelas dari mulut Atif. Namun, penulis bisa menangkap warna, makna, dan pesan di balik suara tadi. Percakapan hangat pun berlangsung, saat guk khas Atif keluar. Sementara itu, awan Dahlan pun larut memangkas rambut penulis. Penulis lebih banyak diam, dengan sesekali bertanya, sembari mendengar guk puisi-puisi yang dilagukan, dan memperhatikan raut wajah, tambah bahasa tubuh Atif.
Atif yang sehari-hari berkerja sebagai toke kopi, memulai didong sejak tahun 1965. Pada saat itu, selain mencipta, Latif sudah menjadi ceh. Suara Latif begitu khas, “merdu” dan enak di dengar. Begitulah harusnya seorang ceh didong di tanoh Gayo. Selain mampu menciptakan lirik didong (puisi), seorang ceh harus memiliki suara yang bagus, dan mampu membawakan lirik-lirik tadi (menjadi vokalis didong). Namun, dewasa ini, kata Atif, banyak ceh yang tidak memenuhi syarat. Lebih banyak ceh-ceh-han. Umumnya ceh sekarang, hanya mampu membawakan lirikan didong. Itu pun karya ceh lain, yang sudah kerap dibawakan dalam didong, atau lagu. Belum lagi, suara-nya yang pas-pas-san. Ceh yang ada sekarang cenderung memaksakan diri, asal disebut ceh. Banyak ceh tidak lagi mampu mencipta, terlebih lagi dengan kandungan nilai-nilai, dan filsafat sastra Gayo yang tinggi. Enti mu lelang empus si nge lapang, kata Atif sambil tertawa. Artinya, jangan membersihkan rerumputan (yang ada di) kebun yang sudah lapang. Sebaliknya, harus mampu menciptakan karya sendiri, tidak plagiat, dan tidak mengklaim karya orang lain jadi milik sendiri.
Bagi Atif, didong harus mampu menjadi sarana pemersatu, dalam menciptakan harmoni sosial di tanoh Gayo, dan Aceh. Bagaimana mau harmoni, dalam perkembangan didong, ceh dan kelop didong sekarang, saling membuka aib. Bahasa yang digunakan, juga bahasa yang “vulgar,” langsung, dan cenderung kasar. Ceh sudah jarang yang berfilsafat, menggunakan filsafat bahasa, bahasa yang santun, dan tidak lagi memakai simbol-simbol. Dalam dunia didong, hal tadi terkandung dalam tamsil, dan ibarat. Begitulah pegeseran nilai, norma, dan budaya dalam didong, dan umumnya budaya orang yang berdiam di tanoh Gayo.
Selanjutnya, didong harus mampu bertindak sebagai sarana pembangunan “pencari dana sosial” (meminjam istilah Melalatoa). Ingatan penulis langsung tertuju pada “Mesejit Mutelong” (Masjid Terbakar), salah satu karya Abdullah Mongal, yang lebih dikenal dengan sapaan Gecik Tue Mongal. “Mesejit Mutelong” ini mengisahkan terbakarnya Mesjid Bebesen (sekarang Mesjid Besar Quba Bebesen yang ada di Takengon), yang dibakar anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), 21 Juli 1965. Ketika itu, pencarian dana pun dilakukan Kelop Kebinet di berbagai tempat di Takengon (termasuk Bener Meriah). Atif sendiri bertindak vokalis, yang dipercayakan membawakan lagu ini. Penonton tak mau ketinggalan, berduyun-duyun menyaksikan pementasan Atif, dan Kelop Kebinet dari kampung Bebesen, sambil bersedekah. Mesejit Mutelong ini begitu menggugah, menyetuh rasa, dan mendorong masyarakat Bebesen khususnya, umumnya masyarakat Takengon, bahkan sampai ke luar daerah, untuk terlibat langsung dalam rekonstruksi, dan rehabilitasi masjid, dan masyarakat Bebesen melalui berbagai bentuk donasi yang diberikan kala itu.
Fungsi yang kedua ini yang sudah jarang diperankan dalam sejarah didong kontemporer di tanoh Gayo. Pementasan terakhir (sepetahuan penulis), dalam bentuk didong jalu (bentuk didong yang dipertandingkan), berlangsung tanggal 21 November 2009 lalu, antara Kelop Sebaya Bujang, dengan ceh-nya Ikhwansyah, dari Kabupaten Aceh Tengah dan Kelop Meriah Dama, dengan Arifin Muslim yang juga bertindak sebagai ceh, dari Kabupaten Bener Meriah. Pementasan ini bertujuan untuk menggalang dana dalam pembangunan Gedung Laboratorium Micro Teaching Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Gajah Putih Takengon, yang lantai dua-nya digunakan untuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan, sekaligus dipakai untuk Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat.
Terakhir, bagi Atif, kesenian tradisional Gayo ini harus mampu menjadi sarana kemajuan. Kemajuan yang dimaksud tidak sebatas pembangunan fisik, melalui penggalangan dana, melainkan non-fisik, baik dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, maupun pola tindak yang “sehat,” dan baik. Kemudian, ceh, melalui karya, dan kelop didong, harus mampu memperkenalkan tanoh Gayo ke luar. Akibatnya, masyarakat luar, tahu potensi yang dimiliki tanoh Gayo. Pada akhirnya, mereka akan berinventasi ke daerah Gayo. Dengan begitu, akan tercipta kesinerjisan dalam pembangunan tanoh Gayo, baik ceh, rakyat, berbagai elemen masyarakat dengan masing-masing potensi yang dimiliki, pemerintah, dan pihak luar.
Dalam amatan penulis, Atif tidak lagi aktif berdidong seperti awal-awal keterlibatannya. Keterlibatannya dalam didong lebih karena pergaulan sosial. Dengan kata lain, Atif tidak menggantungkan hidup sepenuhnya pada didong. Kekurang-aktifannya dalam didong belakangan, dan dewasa ini, karena kurangnya penghargaan kepada ceh-ceh. Para ceh dan kelop didong diperlukan hanya untuk saat, dan keperluan tertentu. Setelah itu, para ceh, dan kelop didong “dicampakkan” begitu saja. Tak jarang, karya ceh banyak yang digubah, “diambil” ceh, atau pihak lain, dengan sengaja, dan tanpa izin “di curi.” Begitu juga dengan pemerintah, yang masih kurang menghargai ceh, terutama yang berkenaan dengan ekonomi ceh “kelangsungan hidup.” Akibatnya, ceh tak mampu fokus, dan total dalam mencipta, dan ber-didong, karena benturan perkara dapur. Umumnya, memang masih belum ada pembangunan kebudayaan, termasuk di dalamnya pembangunan sejarah, dan pembangunan pendidikan yang jelas, tepat, terarah, dan berkelanjutan di tanoh Gayo, khususnya di Takengon. Semua dibiarkan berlalu, dan hilang tanpa ada sentuhan, dan upaya penyelamatan. Walaupun, dewasa ini pergeseran nilai, norma, dan budaya masyarakat Gayo terjadi begitu deras.
Begitulah gambaran kecil pemikiran, dan kontribusi Atif selaku ceh dalam dunia didong di tanoh Gayo, Aceh, khususnya di Takengon dan Bener Meriah. Begitu pula ceh, dan kelop didong lainnya. Keberadaan mereka tutur berkontribusi bagi perkembangan daerah. Sumbangsih pemikiran, dan peran serta ceh dalam didong, berhasil membentuk konstruksi, dan harmonisasi sosial, serta berbagai kemajuan yang dicapai di tanoh Gayo. Bahkan, didong telah pula mengenalkan tanoh Gayo ke dunia luar. Alhasil, melalui didong, nahma, derajat, dan marwah daerah ini, Takengon, tanoh Gayo, dan Aceh turut pula terangkat.
*Pemerhati Kebudayaan Gayo, Mahasiswa Pascasarjana Linguistik Konsentrasi Ekolinguistik Universitas Sumatera Utara (USU) Medan
Oleh Yusra Habib Abdul Gani
Konfigurasi gerak tari Saman, selama ini dipahami orang sebagai kreasi seni tari biasa. Tak hanya bisa dimainkan orang Gayo dalam bahasa Gayo, tetapi juga bisa dipentaskan oleh siapa saja dan dalam bahasa apa saja. Ini kesalahan fatal sekaligus pelecehan terhadap missi dari Saman itu sendiri. Tari sejuta tangan ini tidak bisa dicerna dan dihayati, sekiranya tidak memahami keseluruhan gerak yang diperagakan. Saman adalah tari yang mengandung konsep jihad yang disimbulkan lewat irama dan gerak. Dari komposisi, sjèh (pemimpin) atau disebut juga ‘Pengangkat’ mesti duduk di tengah para pemain yang jumlahnya ganjil (13, 15 atau 17 orang). Sjèh bukan remote untuk menggerakkan orang lain beraksi, tetapi sosok pemimpin yang mesti sinkron dengan aturan main; memimpin sekaligus menjadi orang yang dipimpin. Tari Saman tidak menghendaki terjadi: “Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, sementara kamu mengelakkan diri…” (Q: Al-Baqarah, ayat 44).
Karena tari ini dimainkan dalam bentuk group, maka sjech bukan tokoh tungggal yang dikultuskan. Dia didampingi oleh ‘Pengapit’ (staf) sebelah kiri dan kanan yang berperan membantu gerak maupun syair. Jadi, tari Saman, menolak falsafah ‘individualism’, dan menganut penegakan ‘colletivism’. Kebersamaan harus disokong dan diperkuat oleh tiang penyangga antara sesama anggota. Karena itu, dipasang ‘Penupang’, yang posisinya berada di sisi paling kanan dan kiri. Peranan ‘penupang’ disifatkan sebagai akar tunggang rumput “jejerun” (bahasa Gayo), sebagai simbol kekokohan. Komitmen “Bersatu teguh, bercerai rubuh.” maka jangan ada satu pun anggota yang membuat kesilapan dan kesalahan gerak. Karena akan berimbas dan menghancurkan seluruh gerak dan irama. Jadi, sinkronisasi gerak dan persamaan perasaan sangat diutamakan. Ini berarti, pemimpin baik dalam situasi revolusi atau damai, harus berada di tengah-tengah masyarakat, tidak merasa dirinya sebagai tokoh tunggal, akan tetapi sebagai bentuk kekuatan kolektif yang ditopang oleh jamaah.
Tari Saman dimulai dengan gerak “Rengum”, yakni: suara ngauman dipimpin oleh syèh, senyawa dengan ucapan “salam”. Pada tahap ini, terdengar suara magic berdengung, mengalun bersama ayunan tubuh yang lentur dalam posisi ‘berlembuku’ rapat membujur membentuk garis horizontal, sambil melafadhkan kalimah:
“Hmmmm laila la ho
Hmmmm laila la ho
Hmmmm tiada Tuhan selain Allah
Hmmmm tiada Tuhan selain Allah”
Nada dan gerak “rengum” adalah ‘kasat, ‘takrat’ dan ‘takyin’ untuk memulai tari, agar masing-masing peserta memusatkan kekuatan (concentration). Atasnama kalimat tauhid inilah gerak group bermula. “Rengum” diucapkan dalam suara minor yang mampu menggetarkan jiwa-jiwa yang mati dan perasaan kuyu menjadi garang. Kalimat tauhid ini sengaja disisipkan sjèh Saman (tokoh penemu Saman) sebagai missi jihad dan dakwah Islam lewat tari Saman yang sebelumnya diperankan dalam “Pok Ane-ané” (permainan rakyat yang dimainkan secara bebas). Keseragaman dalam gerak “rengum”, bagaikan sebilah pedang Samurai yang sudah diisi dengan kalimat tauhid untuk melakukan berapa varian gerak berikutnya. Gerak ini menukar rasa ke-aku-an (individualism) kepada rasa ke-kami-an dan akhirnya wujud rasa ke-kita-an (collectivism) dan melarutkan diri masing-masing ke dalam lautan gerak dan irama hidup. Mereka layaknya seperti pasukan lebah menyerang, dimana sang ratu lebah tidak nampak; semua penari adalah komandan dan anak buah. Inilah yang disebut “ratip sara anguk, nyawa sara peluk” (“ratip satu angguk, nyawa satu peluk”). Dalam falsafah Aceh dikatakan: “hudép beusaré, maté beusadjan, sikrék kapan saboh keureunda”. Gerak “rengum”, selain dikenal dalam Saman, terdapat juga dalam pengantar mantra doa untuk menghidupkan ‘pedang berkunci’, yaitu: alat perang yang khas di tanah Gayo. Inilah proses pengenalan diri dalam jiwa masing-masing.
Tahap kedua adalah gerak “Dering”, yaitu: varian gerak yang dimainkan oleh semua penari. Gerak ini diantarkan oleh irama ‘Ulu ni lagu’ ( ‘kepala lagu)’. Para penari akan memasuki tahap memperagakan pelbagai ragam gerak. Proses perubahan dari gerak “rengum” kepada “dering” hanya berlangsung dalam seketita saja. Setelah dirangsang oleh suara syèh, secara perlahan-lahan penari memperagakan variasi gerak tangan, menepuk dada, gesekan badan dan putaran kepala. Pada peringkat ini, suara dan gerakannya masih datar dan lamban.
“Dering” adalah sylabus pengajaran kepada masyarakat yang berbeda tingkat kesadaran, pengetahuan dan pemahaman; tidak ada unsur paksaan, disuarakan dalam bahasa asli (Gayo) yang sopan dan jelas. Barulah kemudian, syèh mengalunkan suara melengking, sekaligus memberi aba-aba akan memasuki tahap gerak cepat. ‘Warning’ itu berbunyi: “Inget-inget pongku male i guncang” (“Ingat-ingat teman akan diguncang”). Inilah klimaks gerakan tari saman, dimana penari secara optimal mengetengahkan varian gerak putaran kepala yang mengangguk (girik), tangan yang menepuk dada dan paha maupun gerakan badan ke atas-bawah, miring ke kiri-kanan bersilang (singkéh) maupun petikan jari (kertèk). Di sini tidak terdapat lirik, irama dan suara. Sepenuhnya aksi. Di tengah kemucak itu, tiba-tiba menyusul gerak “Uak ni kemuh” (“obatnya gerak”) atau gerak neutral yang disenyawakan dengan nada minor yang datar. Saat stamina penari pulih semula, aksi gerak cepat beraksi kembali. Inilah tahap kesaksian dan pengenalan fakta yang disaksikan dengan mata kepala sendiri.
Tahap ketiga adalah: gerak “Redet”. Menampilkan lagu dalam lirik singkat dan jelas. Ianya pesan singkat yang harus didengar sambil menanti arahan selanjutnya. Pengkabaran (informasi) agar orang tahu persis akan pesan yang disampaikan. Yang berarti, manusia adalah pelaku dari informasi yang didengarnya!
Tahap keempat adalah: gerak “Syèh”. Menyampaikan warkah. Pada peringkat ini, syèh mengalunkan lagu dengan suara tinggi melengking dan panjang, sebagai aba-aba akan terjadi pertukaran gerak. Inilah kiat dari roda kehidupan manusia yang sarat dengan perubahan. Penciptaan dan penghancuran; penjajahan dan kemerdekaan; kekayaan dan kemiskinan; kehidupan dan kematian.
Tahap kelima (terakhir) adalah: gerak “Saur” atau penutup. Gerak ini adalah pengulangan bunyi reff yang disuarakan syèh oleh seluruh penari. Ini mengisaratkan tentang bay’ah massal, dedikasi, setia dan taat kepada pemimpin. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa: “Rengum” adalah kesadaran, kesaksian dan komitmen; “dering” berarti introspeksi, pengenalan, pengajaran dan kesopanan; “Redet” adalah pesan singkat, nota penting dan harapan; “Syèh” ialah seruan umum, imamah dan tanggungjawab dan “Saur” yang berarti pernyataan kesetiaan, dedikasi dan kekompakan.
Keseluruhan variasi gerak Saman seperti: guncang, kirep, lingang, surang-saring (semua bahasa Gayo) adalah refleksi dari pesan-pesan, hanya saja orang acuh dan hanya terpaku dengan geraknya. Saman bukan konsep hijrah dan menyerang (ofensive) melainkan konsep bertahan (defensive). Di sini dibuktikan bahwa, refleksi ruh tari Saman terpantul dalam perang melawan Belanda di Kuta Rèh, Penosan, dll tahun 1907. Ketika pasukan Van Dallen merambah masuk ke Gayo Luwes; hanya orang yang sudah melewati “rengum”, “dering”, “Redet”, “Syèh” dan “Saur” saja yang bersabung dengan serdadu Belanda. Selebihnya: anak-anak, perempuan dan lekaki tidak menyelamatkan diri ke dalam hutan. Mereka membentuk gerak Saman dengan cara merapatkan shaff (ingat: barisan penari Saman yang membentuk garis horizontal) dan mengurung diri dalam satu kawasan yang dipagar dengan babu runcing. Tidak mau bergeming. Inilah sumpah tentang: tanah, negara dan kehormatan. Di atas yang bertuah ini kami lahir dan mati dengan darah. Darah adalah rahasia! Dalam konteks ini, Van Dallen berkata: “sepanjang sejarah penaklukan bangsa-bangsa lain, belum pernah kami mendapati orang yang begitu berani dan fanatik, kecuali: orang Gayo.”
Orang Gayo hanya tahu mempertahankan diri, bukan melarikan diri. Itu sebabnya, semasa perang melawan Belanda, mereka tidak menyelamatkan diri ke luar Aceh. Bagaimana aplikasi jiwa Saman dalam situasi sekarang? Haruskah mengisolasi diri dalam pagar “kuta Rèh”?, No! Saatnya orang Gayo Lues menyatukan diri dalam kebulatan tekad dan suara untuk menentukan nasib masa depan Daerah ke arah yang lebih maju dan gerak Saman perlu ditafsirkan semula dalam konteks kehidupan ke-kini-an kita. Insya-Allah!
* Penulis adalah Director Institute for Ethnics Civilization Research
Sumber: serambinews.com, 22 November 2009
Oleh Khalisuddin
6 Nopember 1908, 101 tahun lalu, Cut Nyak Dhien yang paling ditakuti penjajah Belanda berpulang ke Rahmatullah di negeri pengasingan yang nan jauh dari Aceh saat itu, Sumedang Jawa Barat.
Seseorang yang pernah sangat dekat dengan pemilik julukan “Ibu Perdu” ini, dalam perannya sebagai Panyair dalam film dokumenter bertajuk Cut Nyak Dhien, Ibrahim Kadir sang Penyair, putra Gayo yang lahir dan besar di Takengon merasakan layaknya ikut berperang dengan penuh heroik membela agama dan kehormatan jengkal demi jengkal tanah Aceh melawan Belanda kafir bersama Cut Nyak Dhien. Penyair, adalah nafas sebuah perjuangan rakyat Aceh. Ibrahim Kadir sangat bangga dan beruntung pernah menjadi orang kepercayaan Cut Nyak Dhien walau hanya dalam sebuah episode film.
Sangat beruntung, Ibrahim Kadir sang Penyair ternyata tidak begitu sulit di cari. Mengisi hari-hari tuanya, sang penyair dipercayakan menjadi tampuk pimpinan pembangunan Masjid Babussalam Kemili kabupaten Aceh Tengah. setiap waktu shalat wajib tiba, dipastikan Ibrahim ada bersama jama’ah masjid tersebut.
Assalamu’alaikum, ucap kami kepada seorang lelaki tua berpakaian biru dengan peci hitam dikepala yang duduk sendiri di teras Masjid Babussalam Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Aceh Tengah, Kamis (5/11) sore. “Wa’alaikum salam, waktu belum masuk waktu ashar, kalau belum wudhu’ silahkan disebelah sana tempatnya,” jawab lelaki tersebut ramah.
“Iya Ama, sebenarnya kami ingin ngobrol dengan Ama,” kata teman yang bersama saya, Munawardi, seorang pemerhati sejarah Gayo di Aceh Tengah. Ama, bahasa Gayo yang berarti bapak.
Pria pemegang peran Penyair dalam film Cut Nyak Dhien yang diproduksi tahun 1988 dan menjadi film terbaik di piala Citra, ajang penjurian perfilman nasional di tahun yang sama. Film yang disutradarai Eros Djarot tersebut juga menjadi film pertama Indonesia yang ditayang di festival film Chanes Prancis tahun 1989.
Diawali dengan perkenalan dan menguatarkan maksud pertemuan, sesaat kemudian kami hanya mendengar penuturan seniman gaek ini. Dari cara bercerita, Ibrahim Kadir tampak sangat menjiwai perannya dan masih sangat ingat semua yang dialami saat melakoni Penyair dalam film bergengsi tersebut.
Tanggal 6 Nopember, apakah bapak ingat sesuatu ? sesaat pria tersebut tercenung seperti mengingat-ingat sesuatu.
“Aduh, saya ingat. Besok 6 Nopember adalah hari wafatnya Cut Nyak Dhien,” jawab Ibrahim Kadir dengan wajah yang tiba-tiba cerah bersemangat. “Saya sang penyair yang mengumandangkan Allahu Akbar dan menyanyikan Hikayat Prang Sabi untuk membakar semangat pejuang Aceh untuk melawan Ulanda Kape. Saya pernah bertengkar dengan Pang Laot. Saya katakan kepada dia “Hei Panglima Laot!, Dengan senjatamu kamu tidak akan bisa usir Kafir Belanda dari Aceh. Tapi dengan syair-syairku kafir-kafir itu akan tunggang langgang hengkang dari Aceh.”
Apa tugas dan fungsi Penyair dalam perang Aceh ?
Para Panglima boleh mati, akan tetapi penyair tak kan pernah mati. Saat Cut Nya’ Dhien dan para pejuang kelihatan lemah dan turun semangat, serta merta penyair hadir untuk kumandang Azan dan mengaji, dendangkan hikayat Perang Sabi dan pekikkan Allahu Akbar. Ketauhidan para pejuang dan rakyat Aceh yang membuat Kafir Belanda tidak bisa menaklukkan Aceh.
Lalu apa syair yang paling berkesan bagi Bapak ?
Cut Nyak Dhien pernah bertanya kepada saya. Penyair, apa syair yang paling indah ?, saya menjawab Allahu Akbar. Itulah syair yang terbaik di jagat raya ini.
Bagaimana Bapak melihat sosok Cut Nyak Dhien ?
Walau perempuan, Cut Nyak Dhien sangat kuat dan siap berperang lahir dan bathin karena dia adalah sosok yang bersih, imannya kuat. Belanda bisa kuasai raganya akan tetapi takkan pernah kuasai ketauhidan Cut Nyak Dhien serta seluruh rakyat Aceh.
Bagaimana perasaan Bapak saat ikut ambil peran dalam film Cut Nyak Dhien ?
Wah…sangat istimewa, saya seperti berada dalam kejadian sesungguhnya, apalagi saat film tersebut sudah jadi dan diputarkan. Tak terkatakan perasaan saya saat melihat acting saya dalam film tersebut. Saya tak percaya bahwa itu saya.
Bagaimana bisa terpilih sebagai actor ?
Aneh bin ajaib, suatu mu’jizat dalam hidup saya. Saya bertemu Eros Djarot dan kawan-kawan di Hotel Renggali Danau Laut Tawar Aceh Tengah. Saat itu, saya sebagai pelatih Didong yang dipertunjukkan kepada para insan film nasional tersebut. Sebelumnya saya tak kenal Eros Djarot, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Pietrajaya Burnama dan lain-lain. Eros menanyai saya, kita mau buat film Cut Nyak Dhien dan sedang cari pemain untuk Penyair. Apakah bapak bersedia datang ke Sigli ikut di tes dengan peran Penyair ?. Saya menjawab seadanya, bersedia.
Kira-kira satu bulan kemudian, Sekda Aceh Tengah yang dijabat M. Syarif menghubungi saya untuk ikuti tes di Sigli. Kepada Sekda tersebut saya jawab, saya tidak usah ikut, dan tak mungkin lulus. Saya juga tidak punya uang untuk ongkos. Sekda tetap memaksa saya, lalu saya diberi uang, cukup untuk ongkos PP dan makan satu hari. Kalo tidak lulus, harus langsung pulang ke Takengon.
Saya kemudian berangkat seadanya tanpa bawa perlengkapan pakaian. Saya hanya penuhi permintaan Sekda untuk ikut. Tiba di Sigli persis pukul 5 sore. Saya kaget, ternyata Eros Djarot, Slamet rahardjo, Christine Hakim, Pietrajaya Burnama. LK Ara juga sebagai peserta dan puluhan peserta lainnya sudah ada disana. Sesaat kemudian Eros Djarot langsung menuyuruh baca naskah film. Sebentar, sekitar 5 menit dan langsung di tes. Keinginan saya hanya ingin proses tersebut segera berlalu dan langsung pulang ke Takengon. Saya tak baca naskah tersebut dengan baik dengan alasan sebagai orang Aceh sudah faham sejarah Aceh.
Lalu apa yang ditanya Eros Djarot ?
Sebagai rakyat Aceh, bagaimana sikap rakyat Aceh saat melawan Belanda. Saya jawab, ini film Aceh bukan film Jawa, tentu tidak sama. Kalau orang Jawa menyapa tamu, singgah Mas, mau kopi ? silahkan diminum, dan lain-lain. Intinya, Jawa sangat ramah dan lemah lembut. Dan karena sikap seperti itu Jawa bisa dijajah hingga 350 tahun.
Nah kalau di Aceh, orang asing yang datang akan ditanya, so nyoe !, dari pane ?, na Assalamu’alaikum ? Han. Cang laju. Karena orang Aceh seperti itu maka Belanda tak berkutik di Aceh.
Eros kelihatan kaget, dan bertanya kepada rekan-rekannya. Nah, anda lihat, anda lihat. Itu orangnya.
Saya bingung, kenapa dan ada apa dengan saya . Eros kemudian katakan “selesai”. Saya betul-betul bingung saat itu. Apalagi setelah Eros katakan hasil testing diumumkan di Anjungan Mon Mata Banda Aceh. Saya tidak punya uang dan hanya bawa pakaian di badan.
Tak hilang akal, saya melobi LK Ara, jika saya tidak lulus maka LK Ara beri ongkos pulang ke Takengon. LK Ara setuju. Dan jadilah saya ke Banda Aceh.
Setibanya di Anjungan Mon Mata, saya tidak percaya diri untuk masuk. Saya bersama rekan seniman asal Gayo di Banda Aceh, Mursalan Ardy mengobrol saja diluar gedung. Saya tidak tahu jika seluruh pembesar dan tokoh-tokoh Aceh sudah berada di dalam Anjungan. Dari Ahli Adat, Gubernur Ibrahim Hasan, Kapolda Aceh Abullah Moeda, petinggi meliter, para rektor perguruan tinggi dan lain-lain.
Saya sama sekali tidak ikuti prosesi acara tersebut, termasuk saat Eros berpidato dan melaporkan hasil tes actor kepada para undangan yang hadir. “Semua pemeran untuk film Cut Nyak Dhien sudah lengkap. Untuk peran Teuku Umar, Slamet Raharjo, Cut Nyak Dhien oleh Christine Hakim, Pang Laot Pietrajaya Burnama, sebagai Nyak Bantu Rita Zahara. Untuk pemeran Penyair yang menembangkan Hikayat Perang Sabi membangunkan semangat perang rakyat Aceh sudah didapat, yakni dari “Jantungnya Aceh, Tanah Gayo” yakni Ibrahim Kadir.
Para pemeran terpilih dipersilahkan maju ke depan para undangan. Lalu, saat nama saya dipanggil, saya tidak dengar karena saya berada diluar. Sampai seseorang berteriak berulang-ulang, mana Ibrahim Kadir. Saya menjawab, hadir, ada apa ?. Orang itu meyuruh saya masuk. Akan tetapi malah saya spontan jawab, untuk apa ?.
Rekan saya, Mursalan menegur, tidak baik bersikap seperti itu, ayo masuk, ajak Mursalan. Saat berada di pintu Anjungan, Eros menunjuk, itu Ibrahim Kadir, kamu lulus. Saya bingung dan spontan menjawab, Lulus Apa ?.
Kemudian saya minta pengumunan diulang. Belum lagi selesai Eros mengulang pengumunan, Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan mendatangi saya yang masih tetap berdiri di depan pintu. “Ibrahim dari Gayo Aceh Tengah, ke depan kamu,” kata Ibrahim Hasan.
Di depan, saya kemudian dipeluk Ibrahim Hasan sambil berpesan, Bawa nama Aceh, kamu salah satu yang lulus jadi pemeran penting dalam film Cut Nyak Dhien, yakni sebagai Penyair. Gubenur kemudian menyelipkan Rencong Emas ke pinggang saya. Saya menangis terharu. Ibu Gubenur juga ikut-ikutan beri amanah, sebagai putra Aceh saya harus bawa nama Aceh.
Lalu bagaimana dengan rival-rival bapak ?
Hehehe., yang lucu sahabat saya, LK Ara yang mengaku sudah tiga bulan menyiapkan diri untuk terpilih sebagai pemeran Penyair akan tetapi tidak lulus. LK Ara ucapkan selamat kepada saya, tapi sambil berkata, ongkos pulang ke Takengon yang dijanjikan dibatalkan. Saat itu, diantara tangis kami tertawa terbahak-bahak.
Jadi untuk pemeran yang termasuk utama hanya bapak yang dari Aceh ?
Kalau melalui tes resmi iya, tapi ada seorang anak yang berperan sebagai Agam, pemerannya Kamaruzzaman asal Sigli dan sekarang bekerja di Jakarta. Khusus untuk cerita anak ini, saya bingung, sebenarnya anak siapa dia ?, benarkan keponakan Cut Nyak Dhien ?.
Perkiraan saya, anak tersebut adalah anak korban syahid kekejaman Belanda di Tenge Besi Kabupaten Bener Meriah sekarang. Dari tiga orang yang dibuang Belanda ke Sumedang, anak itu adalah salah satunya. Anehnya, tidak adanya catatan sejarah kemana anak itu pergi setelah Cut Nyak Dhien wafat di Sumedang.
Pembicaraan kemudian berakhir seiring dikumdangkannya Azan pertanda waktu Ashar sudah tiba.
Oleh Khalisuddin
Takengon – Hari ini, 7 Nopember 2009 dalam seorang anggota milist berbasiskan komunitas Gayo, arigayo@yahoogroups.com mengucapakan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Aceh Tengah. menurut pengirim ucapan selamat tersebut tanggal 7 Nopember adalah hari jadi Kabupaten yang bermaskot Danau Laut Tawar tersebut.
Pendapat ini didasarkan pada lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.7/DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 58 Tahun 1956 tanggal 7 Nopember 1956. Akan tetapi dari informasi yang dikumpulkan di Takengon, tak ada aktivitas masyarakat dan Pemda setempat untuk merayakan jika memang benar 7 Nopember merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) kabupaten yang berjulukan kota BERLIAN (Bersih, Lestari, Indah dan Nyaman) ini.
Ternyata banyak versi terkait hari jadi Aceh Tengah, pertama menurut Oendang-oendang No. 10 tahoen 1948 dan dikukuhkan kembali menjadi sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-undang No. 7 (Drt) Tahun 1956 dengan wilayah meliputi tiga kewedanaan yaitu Kewedanaan Takengon, Gayo Lues dan Tanah Alas.
Selanjutnya pada 1974 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara melalui Undang – undang No. 4 Tahun 1974. Pemekaran Kabupaten Aceh Tengah kembali terjadi. Pada 7 Januari 2004, Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan Undang -undang No. 41 Tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah dengan ibukota Takengon, sementara Kabupaten Bener Meriah beribukota Simpang Tiga Redelong.
Bila mengacu kepada masa jabatan Bupati pertama Kabupaten Aceh Tengah yang dipangku Abdul Wahab dengan masa jabatan 1945-1949, maka bila bicara kapan hari jadi Aceh Tengah tentu tidak terlepas dari jabatan resmi pertama dalam Pemerintahan Indonesia di Aceh Tengah.
Upaya menyepakati ketetapan hari jadi Aceh Tengah, sepertinya belum pernah dilakukan. Pada 20 Nopember 2008 lalu, Majelis Permusyawaratan Ulama ( MPU) Kabupaten Aceh Tengah dalam rapat Dewan Paripurna Ulama (DPU) MPU Aceh Tengah di Gedung Pendari Inen Mayak Teri Takengon merekomendasikan tanggal 18 Mai sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Aceh Tengah.
Pendapat yang diungkapkan oleh Ketua MPU Aceh Tengah, Tgk. H Muhammad Ali Djadun ini didasarkan dengan diangkatnya Tengku Raja Ma’un menjadi Beusterder Van Bukit atau Landehap Van Bukit pada tanggal 18 Februari 1910. Tengku Raja Ma’un ini merupakan orang Gayo pertama yang mengecap pendidikan formal, yakni pada tahun 1905. Raja Ma’un sendiri adalah keturunan lurus dari Muyang Sengeda Kejurun Bukit I atau generasi ke IX setelah Muyang Sengeda, Raja Ma’un dilahirkan pada tahun 1895 di Kebayakan Takengon.
Mendengar pemamparan panjang Tgk. H Ali Djadun saat itu, Bupati Aceh Tengah Ir H Nasaruddin MM berjanji mengadakan seminar untuk menyimpulkan kapan sebenarnya hari lahir Aceh Tengah. “Pemda sendiri melalui sejarawan asal daerah dingin itu telah lama mencari kapan sebenarnya kelahiran Kabupaten yang beribukota Takengon, akan tetapi belum ada sejarawan yang menyerah data-data terkait, “ kata Nasaruddin saat itu.
Menurut Kabag Humas Setdakab Aceh Tengah, Drs. Windi Darsa, Sabtu (7/11), tidak adanya dilakukan kegiatan bentuk peringatan terhadap hari jadi Aceh Tengah dikarenakan belum adanya kesepakatan konkrit dari pemangku kepentingan.
Seorang pemerhati budaya Gayo di Takengon, Aman Shafa mengungkapkan telah ada tim yang dibentuk Pemda Aceh Tengah beberapa tahun silam untuk menggali sejarah terbentuknya Aceh Tengah. Drs. H Mahmud Ibrahim ditunjuk sebagai ketua tim saat itu. Akan tetapi hingga saat ini tak ada laporan pekerjaan tim tersebut. Aman Shafa berharap agar segera dilakukan penetapan kapan hari jadi kabupaten Aceh Tengah, “Sebuah negeri yang besar tak ada arti apa-apa jika tak menghargai sejarahnya,” pungkas Aman Shafa.[003]
Oleh Sabela Gayo*
Terpilihnya Qory Sandioriva sebagai Putri Indonesia tahun 2009 merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Gayo yang berada di Provinsi Aceh bahkan diseluruh Indonesia. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa dimana dengan persaingan yang demikian ketat, Qory Sandioriva berhasil menyisihkan kontestan putri Indonesia lainnya.
Kecaman yang dilontarkan oleh berbagai kalangan di Provinsi Aceh terutama yang datang dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara tgk Mustafa Puteh, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) merupakan kecaman yang penuh dengan nuansa “sentimen negatif” dengan berkedok islam. Kiya tidak bisa mengukur keimanan seseorang hanya dari pakaian/jilbab yang dipakai, tetapi untuk mengukur kadar keimanan seseorang haruslah dilakukan secara komprehensif dari berbagai sisi dan parameter yang ada. Di satu sisi ulama di Aceh sangat agresif atas terpilihnya Qory sandioriva sebagai Putri Indonesia lantaran tidak memakai jilbab, tetapi sebaliknya pada saat qanun jinayat dan qanun acara jinayat disahkan oleh DPR Aceh, banyak kalangan di Aceh bahkan ulama-ulama dayah yang keberatan diberlakukannya Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Disini saja terlihat inkonsistensi dan perpecahan pendapat dikalangan ulama Aceh sendiri dalam hal penerapan syari’at islam secara kaffah. Bahkan ada seorang ulama dayah Aceh mengatakan bahwa “Qanun Jinayat perlu adanya sosialisasi, harus dipertimbangkan kembali dan jangan diberlakukan secara langsung. Untuk hal yang besar saja seperti qanun jinayat dan qanun acara jinayat, para ulama masih berbeda pendapat tentang perlu/tidaknya diterapkan, tetapi mengapa untuk masalah kecil seperti jilbab, mereka seperti orang yang kebakaran jenggot?. Ulama jangan sampai terlibat bahkan terjebak pada isu-isu yang tidak terlalu penting dan strategis, seperti halnya jilbab tersebut.
Hukum positif di indonesia hari ini masih mengakui bahwa pelaksanaan pemilihan putri Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Dan sepanjang yang kami ketahui belum ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sebuah Lembaga Ulama yang diakui keberadaannya di Indonesia, yang mengeluarkan fatwa bahwa ajang Pemilihan Putri Indonesia haram dan orang yang mengikuti kontes Putri Indonesia dikategorikan hukumnya sebagai orang yang tidak beriman dan sebagainya.
Indonesia adalah sebuah Negara hukum yang mengakui keberadaan agama terutama keberadaan hukum islam sebagai salah satu pilar pembentukan hukum nasional, tetapi sepanjang aturan-aturan islam belum diabsorpsi (diserap) ke dalam hukum positif Indonesia, maka hukum islam hanya mengikat secara personal keislamanan.
Jilbab adalah sesuatu alat penutup kepala kaum wanita yang menurut hukum positif di Indonesia bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan melainkan hanya sebatas hak. Kalau kita mau mengkaji tentang jilbab di Indonesia, pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita mau mengkaji jilbab dari sisi hukum positif Indonesia/dari hukum Islam?, dalam konteks ke-Indonesia-an pemakaian jilbab merupakan hak individu/pribadi yang tidak dapat kita paksakan, pemakaian jilbab harus muncul dari kesadaran pribadi/individu tersebut. Untuk kasus terpilihnya Qory Sandioriva dalam ajang Kontes Pemilihan Putri Indonesia 2009, pemakaian jilbab tidak lazim dilakukan karena ada mahkota/tanda kebesaran yang harus dipakai peserta yang mana apabila memakai jilbab kemungkinan besar penyematan mahkota/tanda kebesaran tersebut menjadi sulit dilakukan.
Memakai jilbab/tidak memakai jilbab adalah masalah khilafiyah yang tidak akan pernah selesai-selesai apabila dibahas, sama halnya dengan permasalahan khilafiyah apakah shalat subuh pakai qunut/tidak. Bagi saya pribadi bukan menjadi permasalahan yang besar apakah orang tersebut pakai jilbab/tidak, yang paling penting bagi saya adalah apakah orang tersebut shalat lima waktu/tidak?, ada orang yang tiap hari pakai jilbab terus tapi perbuatannya justru berkhalwat terus, dan sebaliknya ada juga orang yang tidak pakai jilbab tapi shalat lima waktunya tidak pernah tinggal. Pakai jilbab/tidak untuk memukur kadar keislaman/keimanan seseorang masih sangat relatif sekali dan tidak memiliki parameter yang jelas. Kita jangan sampai terjebak pada simbolisasi-simbolisasi semata tanpa memperdulikan penguatan-penguatan aqidah keislama di tingkat masyarakat luas.
Pendapat negatif, tudingan miring, bahkan penolakan secara sistematis, atas terpilihnya Qory Sandioriva sebagai Putri Indonesia yang bertujuan untuk menjatuhkan citra Qory Sandioriva secara pribadi, apalagi yang dilontarkan oleh berbagai kalangan di Aceh terutama oleh MPU Aceh Utara, HUDA dan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Aceh,Mirzan Fuady dengan mengatasnamakan Aceh merupakan bentuk perbuatan yang “kurang dewasa” dan “kurang bersahaja”. Kalau mau diprotes jangan kontestan Putri Indonesia nya yang dikecam tetapi kecamlah panitia pelaksana Kontes Putri Indonesia dan pihak-pihak lain yang mendukung acara tersebut. Sebagai contoh: “kalau mau memberantas ganja, orang yang tanam ganja yang harus dihukum mati agar orang lain tidak bisa beli/mendapatkan ganja”. Kalau mau mengecam Putri Indonesia, kecamlah Panitia Pelaksana/pihak-pihak yang mendukung agar supaya tidak ada orang yang ikut kontes pemilihan Putri Indonesia”
Kalau memang Pemerintah Provinsi Aceh tidak mau “mengakui” Qory Sandioriva sebagai Putri Indonesia yang mewakili Aceh bahkan tidak merasa pernah mengirimkan wakilnya untuk mengikuti kontes Putri Indonesia sebagaimana yang dilontarkan oleh Munir Fuady di harian Rakyat Aceh edisi Minggu 11 Oktober 2009, berarti Qory Sandioriva adalah Putri Indonesia yang mewakili Gayo, dari Provinsi Aceh.(karena kebetulan saja Tanoh Gayo secara administratif masih berada dibawah pemerintahan provinsi Aceh).
Semoga kasus ini menjadi bahan renungan bagi masyarakat gayo dimanapun berada bahwa pelaksanaan syariat islam tidak hanya ditentukan oleh simbol-simbol belaka tetapi juga harus merupakan cerminan dari pribadi orang yang bersangkutan. Maju terus adinda ku Qory Sandioriva.
* Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Gayo.
Oleh Yusradi Usman al-Gayoni
Reje mu suket sipet; imem mu perlu sunet; petue mu sidik sasat; rayat genap mupakat.
Artinya:
Reje menakar sifat; imem (berurusan dengan) fardu sunat; petue (bersifat) menyelidiki; rayat bermusyawarah (genap mupakat).
Peribahasa tersebut merupakan falsafah kerajaan Linge, di dataran tinggi tanoh Gayo, yang merupakan salah satu kerajaan tua di Aceh, dengan Adi Genali sebagai raja pertamanya. Dalam kerajaan Linge, terdapat empat unsur pemerintahan yang dikenal dengan sarak opat (empat unsur), yaitu reje (raja), imem, petue, dan rayat (rakyat), ditambah pembantu reje lainnya seperti bedel (wakil raja), banta (sekretaris), kejurun, pengulu, pawang, biden, dan hariye . Sebelum orang Gayo menganut Islam, unsur tadi hanya tiga, yaitu reje, petue, dan rayat. Unsur imem bertambah setelah Islam masuk, dan melembaga dalam masyarakat ini. Pertama, reje mu suket sipet. Reje, raja atau pemimpin harus berindak adil terhadap diri, keluarga, lingkungan ketetanggaan, dan rakyat yang dipimpinnya. Dalam bahasa adat, konsep adil tersebut terangkum dalam munyuket gere rancung, mu nimang gere angik (menakar tidak miring, menimbang tidak berat sebelah). Dalam perencanaan, pengambilan, dan pelaksanaan keputusan, reje turut menyertakan pertimbangan unsur pemerintahan lainnya. Terlebih-lebih, pertimbangan imem, akan sangat menentukan keputusan raja. Selain itu, peran reje, dan imem sangat menentukan baik tidaknya keadaan masyarakat. Dengan begitu, reje, tidak boleh sewenang-wenang, otoriter, dan zalim dalam memimpin pemerintahan.
Kedua, imem mu perlu sunet. Imam, lebe, seltan, atau tengku bertugas terkait dengan Islam, baik perkara syariat, perkembangan Islam kontemporer, hubungan sesama rayat, rayat dengan alam, maupun hubungan vertikal rayat dengan Tuhan. Ketiga, petue mu sidik sasat. Petue; orang yang dituakan dalam masyarakat, diangkat dan ditetapkan raja, dikarenakan yang bersangkutan mengetahui seluk beluk masyarakat terlebih lagi soal adat istiadat, norma, nilai, resam, dan peraturen, . Salah satu tugasnya adalah menyelidiki keadaan masyarakat (mu sidik sasat). Hasil penyelidikan tersebut akan dilaporkan kepada raja, sebagai pertimbangan raja sebelum penetapan sebuah keputusan. Unsur yang terakhir, adalah rayat. Rayat semacam lembaga perwakilan masyarakat untuk bermusyawarah, yang tujuannya untuk mencapai kata mupakat (keramat mupakat behu berdele).
Tari saman adalah sebuah tari tradisonal yang berasal dari daerah lokop serbejadi (Aceh Timur) dan Blangkejeren (Gayo Lues). Dalam berbagai sumber sejarah yang ada Tari Saman sebenarnya untuk tingkat Provinsi Aceh berasal dari kedua daerah tersebut yaitu Lokop Serbejadi dan Blangkejeren. Bahkan di Aceh Tengah dan Bener Meriah sendiri yang notabene merupakan daerah Gayo, bukan asal dari Tari Saman. Karena seni budaya yang lebih berkembang di Dataran Tinggi Tanoh Gayo khususnya Aceh Tengah dan Bener Meriah adalah kesenian Didong, Sebuku, dll.
Konon pada mulanya Tari Saman diciptakan oleh seorang ulama yang menyebarkan agama islam yang bernama Syech Saman. Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, seni budaya merupakan salah satu media penyampaian dakwah yang paling efektif bagi penyebaran nilai-nilai dan syiar islam di kala itu. Melalui seni-budaya biasanya masyarakat dengan cepat dan mudah menerima dan memahami pesan-pesan dakwah islam yang disampaikan melalui media seni budaya.
Pada era globalisasi, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, seni-budaya merupakan salah satu media yang paling efektif untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan dunia luar. Sedemikian pentingnya peran seni-budaya sehingga banyak Negara yang melakukan pertukaran delegasi seni-budaya dalam rangka semakin mempererat tali persaudaraan dan kesepahaman diantara sesama bangsa-bangsa di dunia. Karena demikian penting dan sakralnya sebuah identitas budaya bagi sebuah komunitas masyarakat adat sehingga masyarakat adat Bali menjadi resah ketika kelompok-kelompok tertentu di Malaysia mengklaim bahwa Tari Pendet adalah kebudayaan asli Malaysia.
Demikian halnya dengan Tari Saman yang sangat diminati dan disenangi oleh berbagai kelompok masyarakat pada setiap penampilannya. Dimana terbukti setiap kali penonton menyaksikan pementasan Tari Saman selalu berdecak kagum dan memberikan aplus yang luar biasa dalam setiap penampilannya. Kekaguman penonton mungkin dikarenakan oleh gerakan-gerakan Tari Saman yang sangat serempak dan rapi dengan semangat para penarinya yang berapi-api. Tetapi sayangnya sekarang ini, banyak para koreografer-koreografer tari ataupun pencipta-pencipta tari dengan berkedok dan berdalih TARI KREASI BARU, menjiplak, meniru dan mengambil gerakan-gerakan Tari Saman pada intinya dengan menambahkan alat-alat musik tertentu untuk menyamarkan gerakan-gerakan Tari Saman yang dicontoh, ditiru dan diambil tersebut. Kalau namanya Kreasi Baru, seharusnya merupakan tari-tarian yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, yang semula gerakan-gerakan tarinya tidak ada dan tidak dikenal kemudian menjadi ada dan dikenal. Demikian pemahaman saya tentang Kreasi Baru dari segi bahasa, entah apakah pemahaman saya itu sama dengan pencipta-pencipta seni lainnya atau tidak. Wallahua’lam bissawab.
Hal tersebut diatas sebenarnya tidak seberapa dan belum apa-apa jika dibandingkan dengan kondisi terakhir dimana Tari Saman sudah ditampilkan dengan penyampaian syair-syairnya yang tidak lagi memakai bahasa dan baju adat Gayo dan banyak Sanggar Tari di Aceh yang sudah mengubah syair-syair Tari Saman kedalam bahasa-bahasa lain selain Bahasa Gayo, bahkan para penari-penarinya pun sudah memakai baju adat lain dan tidak lagi memakai baju adat Gayo. Kondisi itu tentu sangat menyedihkan dan menyakitkan perasaan ke-Gayo-an kita dimana Seni Budaya kita khususnya Tari Saman sudah dibajak oleh orang lain dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Gerakan-gerakan tarinya ditiru, dijiplak dan diambil tetapi identitasnya berupa bahasa dan baju adat ditinggalkan. Dan hal itu terjadi di depan mata kita, tetapi mengapa kita hanya diam saja?.
Kita tidak ingin kondisi Tari Saman akan bernasib tragis sama seperti Tari Pendet dimana Negara lain mengklaim bahwa Tari Pendet itu adalah miliknya. Tapi kalau kita mau jujur Tari Pendet masih lebih untung dan baik kondisinya dibandingkan dengan Tari Saman. Kalau Tari Pendet, hanya kepemilikannya saja yang diklaim oleh Negara lain tapi gerakan-gerakan tarinya, baju adatnya, bahasa penyampaian syair-syairnya masih menggunakan bahasa bali dan memakai baju adat Bali (walaupun menurut kita baju adat Bali itu melanggar syari’at). Tetapi kalau Tari Saman kondisinya lebih parah lagi, gerakan-gerakan tarinya ditiru / dipelajari / dijiplak / diambil, baju adatnya ditukar dan bahasa penyampaian syair-syairnya pun ditukar ke dalam bahasa lain dan baju adat lain. apabila kondisi ini terus-menerus kita biarkan dan kita anggap enteng bukan tidak mungkin suatu saat nanti Tari Saman akan diklaim menjadi milik orang lain dan bukan lagi milik masyarakat Gayo?, masuk akal kan?. Kalau lah seandainya Tari Saman diklaim menjadi milik orang lain tetapi gerakan-gerakan tarinya, bahasanya masih menggunakan bahasa Gayo, dan para penarinya pun masih memakai baju adat Gayo, mungkin kita tidak terlalu sedih tetapi sekarang kondisinya tidak demikian.
Datu orang Gayo menciptakan Tari Saman dengan perpaduan gerakan-gerakan yang serempak dan enerjik dan kemudian memiliki daya tarik tersendiri bagi orang yang menyaksikannya mungkin merupakan suatu karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada masyarakat Gayo. Karena itu masyarakat Gayo harus mensyukuri karunia, rahmat dan pemberian Allah SWT tersebut dengan cara menjaganya, merawatnya, mengembangkannya dan melestarikannya. Sama seperti halnya dengan anak/mobil, ketika kita memperoleh karunia oleh Allah SWT berupa seorang anak maka tentunya kita akan menjaganya, merawatnya, melindunginya dan memberikan pendidikan yang layak baginya. Itu adalah bentuk rasa syukur kita atas karunia Allah SWT tersebut. Kalau rasa syukur itu tidak kita lakukan berarti kita termasuk orang-orang yang tidak mau bersyukur!. Bukankah Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya “ Apabila engkau bersyukur akan nikmat-Ku maka niscaya akan kutambah nikmat itu, tetapi apabila engkau ingkar, ingatlah sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.
Kasus pembajakan Tari Saman ini dapat kita jadikan sebagai bahan renungan dan instropeksi diri, apakah kita sebagai orang Gayo selama ini telah bersyukur kepada Allah SWT dengan segala karunia, rahmat dan pemberian-Nya? Baik itu berupa tanah pertanian yang subur, seni tari yang indah, bahasa yang luar biasa dan budaya serta peradaban yang tinggi. Coba bayangkan jika gerakan-gerakan Tari Saman sudah ditiru/dijiplak/diambil, baju adat dan bahasa penyampaian syair-syairnya pun sudah diubah, bagaimana orang lain bisa mengenal dan mempelajari bahasa, seni dan budaya Gayo ?. bagaimana orang lain bisa tahu kalau diatas bumi ini ada yang namanya Suku Gayo?. Dan mungkin juga Tari Saman itu merupakan suatu jalan yang diberikan oleh Allah SWT bagi orang Gayo untuk bisa dikenal secara luas oleh masyarakat-masyarakat lain di dunia melalui jalur seni dan budaya. Tetapi pada kenyataannya hari ini, gerakan-gerakan Tari Saman sudah ditiru, dijiplak bahkan diambil kemudian bahasanya dan baju adat para penarinya sudah diubah sedemikian rupa oleh kelompok-kelompok tertentu dengan seenaknya, jika kondisi itu terus kita biarkan dan kita menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar-wajar saja maka berarti kita adalah termasuk manusia yang tidak bersyukur tadi dan tidak mempunyai tanggung jawab moral terhadap kesenian kita sendiri. Dan bukan tidak mungkin apabila kita lalai, suatu saat nanti Tari Saman akan diklaim menjadi milik kelompok masyarakat lain.
Bahkan sekarang ini sudah ada opini yang berkembang bahwa seolah-seolah Tari Saman itu adalah milik sekelompok masyarakat tertentu. dan ada sebuah proyek pendidikan di Aceh yang di danai oleh USAID DBE 2 yang mengembangkan Tari Saman bukan dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Gayo dan para penarinya pun tidak memakai baju adat Gayo. Bahkan mereka membuat VCD yang berisi instruksional Tari Saman dalam bahasa Aceh, Inggris dan Indonesia dan disebarkan ke Sekolah-Sekolah Dasar di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, dan Aceh Tengah agar dapat dipelajari oleh siswa-siswa SD yang notabene adalah generasi penerus. Yang apabila kondisi ini dibiarkan maka anak-anak SD yang ada di Gayo akan mempelajari Tari Saman dalam bahasa lain yang sebenarnya asal Tari Saman itu adalah dari Gayo. Ini sangat ironis sekali. dan mereka beralasan mengapa mereka lakukan seperti itu karena bahwa “kondisi yang demikian yang sekarang terjadi secara nyata di lapangan dimana Tari Saman sudah ditampilkan bukan lagi dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Gayo dan para penarinya pun sudah tidak lagi memakai baju adat Gayo”. Alasan yang demikian itu, tentu saja semakin memompa semangat kita untuk mengadvokasi Tari Saman secara sistematis. Sebelum hal itu terus berlanjut maka kita sebagai generasi muda Gayo harus mengambil langkah-langkah penyelamatan baik secara hukum maupun non hukum, di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan dalam rangka mengembalikan marwah dan identitas kita sebagai sebuah komunitas yang kaya akan seni dan budaya. “Kalau warisan datu kita yang sudah ada saja, yang berupa Tari Saman tidak bisa kita jaga, saya kira kita jangan bermimpi untuk meraih sesuatu yang sama sekali belum ada”.
Gerakan penyelamatan Tari Saman yang akan kita lakukan bukan bermaksud untuk melarang agar Tari Saman jangan ditampilkan oleh orang lain/kelompok lain. Bahkan sebaliknya kita sebagai masyarakat Gayo akan semakin bangga mengaku bahwa kita orang Gayo karena memiliki seni-budaya yang indah dan diminati oleh orang lain. Dan juga gerakan penyelamatan Tari Saman yang akan kita lakukan bukan untuk memunculkan konflik baru di tengah-tengah masyarakat/mengkotak-kotak
kan masyarakat antara satu dengan yang lainnya. Tetapi gerakan yang akan kita lakukan adalah murni gerakan penyelamatan seni-budaya dalam rangka melindungi aset seni dan budaya GAYO agar tetap lestari sampai ke akhir zaman. Jadi kita tidak perlu “kemel” atau merasa ini hal yang tabu untuk diadvokasi. Dan Tidak ada unsur-unsur sentimen kesukuan/primordial dalam gerakan ini. Kapan lagi bahasa Gayo mau dipelajari oleh orang lain kalau bukan melalui Tari Saman? Dan kapan lagi budaya Gayo akan dikenal oleh kelompok masyarakat lain kalau bukan melalui Tari Saman?, Apakah ketika Tari Saman yang dibawakan dengan bahasa lain dan baju adat penarinya juga lain, namanya tetap Tari Saman?. Atau namanya berubah menjadi Tari Samin? Atau bahkan Tari Samun?, wallahu’a’lam bissawab.
Bukankah ketika salah satu irama lagu Peterpen yang dinyanyikan oleh penyanyi India dalam bahasa India dengan irama musik yang sama dengan yang dimiliki oleh grup musik Peterpen beberapa waktu yang lalu, itu sudah dikategorikan sebagai sebuah bentuk pembajakan? Apa bedanya dengan kondisi Tari Saman hari ini?. Kalau kondisi seperti ini terus kita biarkan dimana setiap sanggar tari di Aceh yang membawakan/menampilkan Tari Saman selalu menggunakan bahasa dan baju adat lain dan tidak menggunakan bahasa dan baju adat Gayo.maka cepat atau lambat Tari Saman akan menghilang dari Gayo, sama halnya dengan kondisi bahasa Gayo yang hampir punah. Sungguh tragis!!!.
Oleh Yusradi Usman al-Gayoni
“Unang-unang seringkel kampung, lapah ni denung sara ine diri” merupakan salah satu pribahasa Gayo. unang=jalan-jalan; seringkel=keliling; lapah=sayat; denung= lindung (monopterus albus), salah satu jenis ikan di tanoh Gayo, Propinsi Aceh.
Maknanya, sebuah perumpamaan (metapora), sekiranya pun banyak negeri yang kita jejaki (singgahi /tempati), berkenaan dengan perbaikan negerinya, hanya orang tempatan-lah (yang bersangkutan) yang bisa memperbaiki negerinya sendiri.
Begitu pula halnya dengan kita (orang Gayo), tidak ada orang lain bisa memperbaiki tanoh tembuni (tanoh Gayo), selain orang Gayo itu sendiri.
Konsep yang sama ditegaskan pula dalam salah satu surat dalam al-Quran, “hanya kaum itu sendiri yg dapat merubah nasibnya sendiri.” katakanlah, dalam hal penyelamatan lingkungan hidup.
Salah satunya Danau Laut Tawar melalui otorita Danau Laut Tawar, hanya kita (masyarakat tempatan/orang Gayo) yang bisa menyelamatkan danau dan hutan yang ada di tanoh Gayo dari kerusakan, terutama Pemkab serumpun (Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Bener Meriah).
Terlebih lagi Pemkab Aceh Tengah selaku kabupaten induk yang harus berinisiatif lebih dahulu (bekekire, ken perawah, nemah ulu, dan be kejang payah), tambah hal lain, seperti; pembangunan pendidikan yang berkualitas pada semua tingkatan melalui program S-1/2/3, pembangunan dan pemertahanan kebudayaan, pemaksimalan pendokumentasian sejarah, dan apa pun yang bertalian dengan urang Gayo/tanoh Gayo, menggalakan penghargaan, dan budaya berterima kasih terhadap tokoh-tokoh yang telah membesarkan nahma, dan marwah tanoh Gayo, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi, pembangunan pertanian&perternakan yang tepat arah, peningkatan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah yang manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat bawah, dan lain-lain.
Dalam hal yang lebih kecil, sedekat apa pun hubungan kita dengan orang lain, berkenaan dengan hal ikhwal/prinsip, suatu masalah harus diselesaikan dengan anggota keluarga sendiri/yg se darah (sara rayoh).
Oleh: Win Wan Nur
Tiga hari tidak membuka internet tiba-tiba halaman facebook saya dipenuhi kontroversi soal terpilihnya wakil Aceh, Qory Sandioriva, menjadi Puteri Indonesia 2009.
Bagi saya pribadi, ajang pemilihan Puteri Indonesia, Miss Universe dan sejenisnya tidak lain hanyalah kontes adu keindahan daging (fisik) yang dibungkus dengan kemasan yang membuatnya seolah-olah juga merupakan kontes kemampuan intelektual. Bagi saya ini tidaklebih dari sekedar urusan selangkangan yang dibungkus dengan segala gemerlap dunia pertunjukan. Ajang semacam ini sama sekali tidak pernah menarik perhatian saya.
Pandangan pribadi saya terhadap kontes adu keindahan daging yang dilabel dengan nama pemilihan Puteri Indonesia ini sama sekali tidak berubah, meskipun kali ini yang dinobatkan menjadi pemilik daging terindah mengaku sebagai wakil Aceh, daerah asal saya. Bahkan lebih khusus lagi, konon lagi katanya si pemilik daging indah yang bernama Qory ini adalah orang Gayo, sama seperti saya.
Selama ini saya tidak pernah kenal nama Qory dan juga nama kedua orang tuanya, saya baru tahu ada seorang manusia bernama Qory Sandioriva ketika berita kemenangannya membuat heboh dimana-mana. Meskipun jika kemudian orangtuanya bertemu dengan saya dan menanyakan silsilahnya pasti langsung ketemu entah siapanya punya hubungan entah apa dengan salah satu kerabat saya. Itu terjadi karena orang Gayo jumlahnya memang sedikit sekali di planet ini, hanya sekitar 300 ribu orang saja. Jadi antara satu orang Gayo dengan orang Gayo lainnya biasanya selalu ada hubungan kekerabatan.
Intinya penobatan Qory Sandioriva, menjadi Puteri Indonesia 2009 kemarin sama sekali tidak membawa pengaruh apapun bagi saya baik pribadi saya sebagai seorang individu maupun pribadi saya sebagai bagian dari orang Aceh dan lebih khusus lagi Gayo. Kemenangan Qory Sandioriva dalam kontes adu keindahan daging kemarin sama sekali tidak membuat saya sebagai orang Gayo merasa bangga atau terhina, biasa saja!
Yang menjadi masalah adalah, hanya sedikit sekali orang Aceh dan orang Gayo yang memiliki sikap seperti saya yang menganggap remeh masalah selangkangan.
Bagi kebanyakan orang Aceh dan juga orang Gayo, masalah selangkangan ada di urutan tertinggi dalam daftar moralitas yang harus diatur dengan ketat dan sungguh-sungguh. Sampai saat ini tidak sedikit orang Aceh yang percaya kalau Tsunami yang meluluh lantakkan Aceh yang terjadi tahun 2004, bisa terjadi akibat orang Aceh tidak bisa menjaga selangkangan.
Bahkan hanya beberapa hari yang lalu seorang perempuan asal Gayo, putri seorang pejabat tinggi di pemda Aceh Tengah yang mengenyam gelar sarjana teknik sipil dan selalu berjilbab menulis di statusnya di ‘facebook’. “Mungkin Allah sengaja membakar gunung-gunung di sekitar danau Laut Tawar karena Allah marah bukit-bukit itu dijadikan tempat berkhalwat”.
Sebagaimana para penyembah berhala di segala zaman yang selalu menggambarkan Tuhan seperti sosok dirinya. Orang Gayo yang menulis status di facebook inipun menggambarkan Tuhan yang dia sebut dengan nama yang sama seperti nama Tuhan dalam setiap ibadah yang saya lakukan ini pun persis seperti sosok dirinya yang merasa begitu pentingnya urusan selangkangan. Tuhan dia gambarkan sebagai sosok yang cepat sekali marah dan emosi melihat ada orang yang tidak mampu menjaga selangkangan, tapi punya segudang alasan dan pemakluman untuk berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan oleh penguasa. Bahkan bisa memaklumi pejabat yang menjual dan ulama yang menyetujui penjualan Mesjid dan Panti Asuhan. Sosok Tuhan di statusnya ini tampak persis seperti fotocopy diri perempuan ini sendiri.
Apa yang saya ceritakan di atas adalah gambaran tentang begitu pentingnya urusan selangkangan ini di dalam masyarakat Aceh dan Gayo. Sehingga ketika Qanun Syari’at Islam dibuat dan diterapkan di negeri ini pun, masalah yang paling banyak diatur dalam Qanun (undang-undang) ini adalah urusan selangkangan.
Menilik pada kenyataan itulah maka sayapun sama sekali tidak merasa heran ketika kemenangan Qory Sandioriva dalam kontes adu keindahan daging yang baru lalu manarik atensi dan menimbulkan pro kontra di semua kalangan.
Di kalangan ulama dan para pendukung Syari’at Islam dan para moralis jelas, Qory yang tidak berjilbab yang memenangi kontes adu keindahan daging se Indonesia dalam kapasitasnya sebagai wakil negeri mereka ini adalah sebuah tamparan. Sebaliknya bagi yang menentang penerapan syari’at ini menjadi bahan baru untuk melakukan perlawanan.
Tidak ketinggalan para oportunis yang ingin mendirikan provinsi baru di Aceh yang sempat beberapa lama mati suri karena isu usang yang mereka usung tidak lagi mendapat tanggapan memadai dengan dengan sigap memanfaatkan momen terpilihnya Qory Sandioriva dalam kontes adu keindahan daging ini untuk membangkitkan sentimen keGayo-an yang berbeda dengan Aceh.
Pejabat pemerintah dengan segala keterbatasan wawasan, keterbatasan kecerdasan dipadu dengan keluguan dan kenaifannya mencoba menyangkal ‘Keacehan’ Qory melalui status kependudukannya yang tidak ber KTP Aceh. Ini sangat lucu karena jika standar yang coba dibuat oleh si pejabat ini tentang ‘keacehan’ seseorang yang dinilai dari status kependudukan di KTP ini benar-benar diterima sebagai standar resmi untuk menilai kadar keacehan seseorang. Maka saya yang lahir dan besar di Aceh dari ibu dan bapak asli Gayo akan menjadi bukan orang Aceh. Tgk. Hasan Tiro, Mentro Malik dan Surya Paloh yang tidak memiliki KTP Aceh juga tiba-tiba menjadi BUKAN ORANG ACEH. Sebaliknya justru si Pinem, Hutabarat, Surono, Paiman dan A Hong yang ber KTP Aceh adalah orang Aceh yang asli.
Soal karena tidak ber-KTP Aceh tapi malah mewakili Aceh di sebuah ajang. Dulu waktu saya masih duduk di bangku SD juga ada seorang atlit lempar lembing bernama depan Tati kalau tidak salah yang berKTP Jawa Barat tapi dalam PON selalu memilih mewakili Aceh dan menyumbangkan emas untuk provinsi ini, saat itu tidak ada polemik seperti ini. Tidak ada satupun orang Aceh yang meragukan dan mempermasalahkan keacehannya meskipun dalam kapasitasnya sebagi atlet lempar lembing dia tidak berjilbab dan malah berpakaian minim.
Jadi sebenarnya urusan KTP seperti yang disinyalir oleh pejabat lugu yang kurang cerdas ini bukanlah masalahnya.
Pasca kemenangan Qory Sandioriva,seorang teman saya yang bekerja sebagai wartawan mengamati fenomena obrolan yang terjadi di warung-warung kopi yang merupakan pusat peradaban di Aceh.
“Para penonton di warung tersebut dengan tekun mengikuti wawancara di layar kaca tersebut. “Qory bukan orang Aceh” kata seorang tamu di warkop tersebut dalam bahasa Aceh. Tapi kemudian seorang tamu lainnya nyeletuk, “bagaimana dengan kondisi Aceh sekarang dan penampilan artis-artis asal Aceh lainnya, apa sudah sesuai Syar’at Islam,” belasan tamu di warkop tersebut terdiam.”, begitu tulis teman saya ini dalam laporannya.
Soal polemik Qori ini, saya juga membaca berbagai blog milik sebuah media terbitan Medan lengkap dengan berbagi komentar pembacanya.
Blog itu memuat sebuah kalimat yang menggambarkan tentang Qory seperti di bawah ini.
Sebagai seorang wanita keturunan Aceh Gayo, Qory mengaku mengidolakan Tjut Nya’ Dhien, tokoh pahlawan wanita Aceh yang mampu bersikap Islami dalam keseharian walaupun tidak menggunakan jilbab. “Dialah panutan saya selama ini. Selain dengan sikapnya yang heroik, Tjut Nya’ Dhien merupakan tokoh pahlawan wanita Islami, walaupun dalam kesehariannya, dia tidak menggunakan jilbab,” ujar Qory.
Ucapan Qory ini langsung memantik reaksi kemarahan banyak orang. Ada yang menyebut “tentang gambar cut nyak dien yg tak berjelbab tu adalah gambar ilustrasi penjajah”. Yang lain malah langsung menegasikan ‘kegayoa-an’ Qory “Dia bkan awak Gayo’ tpi dia jema sunda. Jelas. . Jdi gw juga gk sependapt dgn ucpan pling atas.” begitu menurut komentator kedua. Yang lain mengatakan “siapa bilang pahlawan aceh cut nyak dhien tidak pakai jilbab..!!jangan liat yang di film2 donk..membenarkan kesalahan kamu dengan memfitnah orang…”
Entah dari ikhwan PKS mana si komentator ini dapat data itu, dan entah sejak kapan dia pernah tinggal di Aceh sehingga bisa membuat statement semacam itu. Karena saya yang sejak lahir tinggal di Aceh yang sempat tinggal dengan Datu Anan (ibu dari kakek saya) yang lahir di tahun 1800-an (pada zaman Cut Nyak Dhien masih hidup) sama sekali tidak pernah melihat Datu saya tersebut dan perempuan-perempuan Gayo seangkatannya mengenakan jilbab. Malah ibu-ibu dan gadis-gadis Gayo yang menggeraikan rambut di depoan pintu menggosip sambil mencari kutu adalah pemandangan umum yang saya saksikan setiap hari di seantero kampung saya. Kemudian pakaian adat yang dikenakan perempuan Aceh dan Gayo-pun sama sekali tidak dilengkjapi Jilbab (bayangkan bagaimana sulitnya memasang ‘kepies’ di atas Jilbab).
Cara pandang Islam yang ketat dan kaku sebenarnya baru dikenal di Gayo pada masa-masa pengujung kekuasaan Belanda melalui para Teungku yang kembali dari belajar agama di tanah Minang, dan paham seperti itu sama sekali tidak familiar bagi perempuan Aceh generasi Cut Nyak Dhien dan generasi Datu Anan saya.
Tapi meskipun tidak berjilbab, bukan berarti orang Aceh dan Gayo juga menolerir pemakaian bikini. Budaya Aceh dan juga Gayo punya batasan sendiri soal kepantasan dan kepatutan berpakaian perempuan, yaitu tidak berpakaian ketat apalagi sampai menampakkan dada dan paha. Batasan ini bertahan sampai generasi saya. Saat saya masih kuliah, meskipun tidak berjilbab, teman-teman saya tidak satupun yang pernah saya lihat mengenakan rok pendek. Jangankan rok mini, bahkan sekedar yang mengenakan rok yang menutupi lutut seperti rok anak SMA pun tidak ada. Jika saya perhatikan sikap teman-teman saya it, saya lihat mereka tidak merasa nyaman dan merasa menjadi objek seksual jika mengenakan pakaian ketat apalagi rok mini yang menampakkan paha. Semasa kuliah, yang sering saya lihat berpakaian ketat nan menantang cuma cewek-cewek anak ekonomi yang tampaknya berusaha keras agar berpenampilan seperti anak Jakarta. Tapi seberani-beraninya anak ekonomi tidak ada yang sampai berani memaki rok mini.
Laki-laki Aceh sendiri meski tentu saja tergiur dan suka melihat cewek seksi memakai rok mini, tapi pada dasarnya laki-laki Aceh juga tidak merasa nyaman melihat perempuan Aceh mengenakan rok mini. Di masa saya kuliah dulu, bisa saya pastikan tidak seorangpun teman saya yang merasa nyaman menggandeng pacar seksi yang menggunakan rok mini di depan teman-temannya apalagi orangtua.
Beberapa waktu yang lalu saat saya berada dalam ferry dari Jawa menuju Bali saya melihat sebuah foto yang dimuat di koran Jawa Pos.
Foto ini adalah foto sensasional karya seorang fotografer jempolan sekaligus degil, dalam foto ini terlihat seorang model cantik yang difoto telanjang di atas kereta api di tengah padatnya penumpang. Dalam foto itu terlihat betapalaki-laki dari berbagai kalangan dan usia melotot dan membelalak tergiur meyaksikan pemandangan segar di depan mata. Foto itu diambil ketika si model yang mengenakan jas panjang tiba-tiba melepas jasnya dan tidak mengenakan apa-apa di baliknya. Proses ini berlangsung hanya 35 detik saja tapi cukup menggambarkan bagaimana reaksi para pria yang berada dalam kereta api untuk berangkat kerja ketika disuguhi pemandangan indah tubuh wanita.
Ketika diwawancarai soal ini dan si pewawancara menanyakan, apakah si fotografer tidak berniat membuat foto yang sama dengan model pria ditengah para penumpang wanita. “Tidak” jawab si fotografer. “pria berbeda dengan wanita, kalau pria tersenyum dan tertawa melihat perempuan telanjang, sebaliknya wanita akan menjerit karena merasa diintimidasi jika melihat laki-laki menunjukkan kemaluannya, bisa -bisa saya malah dituntut dan masuk penjara”, begitu komentar si fotografer.
Beberapa kaum feminis kesiangan pernah mengaitkan masalah pamer fisik ini ketidak adilan jender. “Puteri Indonesia berpakaian minim dipermasalahkan, kenapa Ade Rai pamer otot tidak pernah dipermasalahkan?” kata si feminis kesiangan ini. Padahal seperti yang dikatakan si fotografer di atas, bukan soal ketidak adilan, tapi dalam urusan rangsangan seksual saat melihat tubuh lawan jenis, laki-laki memang berbeda dengan perempuan.
Dikaitkan dengan polemik kemenangan Qory di ajang kontes adu keindahan daging kemarin, yang saya lihat dari fenomena pro dan kontranya kemenangan Qory ini bukanlah karena Qory terpilih sebagai puteri Indonesia dan tidak mengenakan jilbab pada saat penobatannya. Tapi lebih kepada keikut sertaan Qory nantinya di ajang Miss Universe yang mengharuskan pesertanya mengenakan bikini. Ketidaknyamanan orang Aceh dan sebagian orang Gayo atas kemenangannya dalam kontes adu keindahan daging ini adalah ketidak nyamanan ketika orang Aceh membayangkan ada seorang perempuan yang mengaku sebagai wakil ACEH mengenakan bikini memamerkan paha dan dadanya dan menjadi objek seksual di depan jutaan pasang mata.
Lebih jelasnya, menurut saya masalah Qory Sandioriva menjadi polemik bukanlah soal status keacehannya atau apa. Tapi karena Qory yang mengaku mewakili Aceh menang dalam sebuah lomba yang identik dengan urusan SELANGKANGAN. Urusan yang merupakan urutan tertinggi dalam daftar moralitas masyarakat Aceh dan Gayo.
Aceh sanggup mempertahankan keharmonisannya dengan Gayo ketika hubungan Aceh-Gayo diterpa isu ketidakadilan pembangunan, isu pilih kasih soal jabatan, isu pembajakan budaya (mirip seperti hubungan Indonesia-Malaysia). Tapi jujur saja, saya ragu keharmonisan hubungan Aceh-Gayo ini bisa bertahan ketika berurusan dengan isu SELANGKANGAN.
Untuk Qory sendiri dan juga keluarganya saya berharap mereka tidak cukup bodoh untuk tidak mempertimbangkan resiko yang telah mereka tempuh dengan memberanikan diri mengikuti kontes adu keindahan daging mewakili Aceh. Dengan keberanian Qory mengikuti ajang ini dengan mewakili Aceh dan direstui pula oleh keluarganya, saya berasumsi bahwa Qory dan keluarganya sudah mempertimbangkan semua hal termasuk mempetimbangkan kenyataan tentang betapa sebagian sangat besar masyarakat yang telah dengan berani dia wakili itu masih sangat konservatif terhadap bilai-nilai tradisional. Yang bisa sangat marah dan emosi dan mungkin akan melempari rumah dan mengintimidasi keluarga Qory.
Dalam kasus ini kita tidak bisa menyebut apa yang dilakukan Qory adalah hak pribadi untuk menjalankan agamanya, mengekspresikan dirinya sesuai dengan nilai dan pemahaman agama yang dia akui.
Wassalam
Win Wan Nur
Orang Gayo
http://www.winwannur.blog.com
http://www.winwannur.blogspot.com
Oleh Khalisuddin
Sedikitnya ada tiga hal yang menjadi permasalahan besar di Gayo yang bila tidak ditangani serius akan menyebabkan percepatan hilangnya suku Gayo dari permukaan bumi, demikian pernyataan budayawan Fikar W Eda dalam sebuah diskusi informal sejumlah tokoh pemuda dan mahasiswa yang diselenggarakan di pekarangan Hotel Buntul Kubu Takengon (22/9) sejak sore hingga menjelang tengah malam.
Dinyatakan Fikar, ketiga persoalan yang perlu diperhatikan tersebut diantaranya persoalan punahnya kebudayaan Gayo, rusaknya lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum.
Menurut Fikar yang juga wartawan di Jakarta ini, bahasa, seni, ilmu pengetahuan dan segala bentuk yang diciptakan oleh orang Gayo merupakan defenisi budaya Gayo. Fikar memvonis budaya Gayo akan hilang dari muka bumi karena dari masa ke masa tidak ada upaya konkrit dan terpadu untuk melestarikannya.
Dicontohkan Fikar dengan mencatut nama Bupati Bener Meriah, Ir. Tagore AB. “Yang membedakan Tagore yang orang Gayo dengan Tagore di India adalah budaya. Nama, gaya dan lain-lain bisa saja sama, tapi budaya pasti beda,” kata Fikar.
Terkait lingkungan hidup sebagai persoalan besar kedua di Gayo, Fikar mencontohkan kondisi danau kebanggaan masyarakat Gayo, danau Laut Tawar.
“Melihat kondisi ekosistim Laut Tawar dari tahun ke tahun yang semakin memburuk, bukan tidak mungkin suatu saat ditengah Laut Tawar sekarang akan berdiri rumah-rumah penduduk dan saat itu keberadaan Laut Tawar hanya menjadi dongeng,” kata Fikar.
Gejala-gejala berubahnya Laut Tawar sudah tampak sekarang, kata Fikar dengan mencontohkan akibat turunnya debit air danau, air sungai Peusangan menjadi sangat berkurang sehingga ada bagian sungai yang sudah kering dan dapat dijadikan sebagai lapangan volley ball.
Terakhir dibidang penegakan hukum, Fikar berpendapat orang Gayo sejak dulu sangat takut bila harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Karena budaya ini, penegakan hukum di Gayo menjadi mandul terutama terkait perkara tindak korupsi.
“Persoalan berlebihnya 5 kursi di DPRK hasil Pileg 2009 merupakan perkara kriminal, kenapa tidak diproses sebagai perkara pidana,” kata Fikar mencontohkan dan bernada tanya.
Pendapat Fikar ini langsung ditanggapi Akhiruddin Mahyuddin, koordinator Gerak Aceh yang sedang berlebaran di Takengon sebagai kampung halaman sang istri. Dikatakan Akhiruddin, di Gayo perlu dilakukan kampanye anti korupsi yang lebih gencar lagi seperti yang dilakukan oleh Jaringan Anti Korupsi (Jang-Ko) selama ini.
“Gerakan Jang-Ko akan hilang sebentar lagi bila tidak didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta dukungan jaringan. Harus ada komponen pendukung agar daya tekan lembaga-lembaga anti korupsi di Tanah Gayo lebih berarti,” kata Akhiruddin yang kini sedang menyelesaikan pendidikan strata dua di Universitas Indonesia (UI) ini.
Diakui Akhiruddin, walau Gerak sudah beberapa kali eksis mengangkat kasus korupsi di daerah lain di Aceh akan tetapi di Gayo belum pernah.
“Perlu upaya keras untuk ungkap kasus korupsi disini dan kita sama-sama mendukung dan berharap agar Idrus, Hamdani dan kawan-kawan lain dari Jang-Ko untuk jangan berputus asa. Targetkan satu kasus walau kecil sampai tuntas sehingga kedepan Jang-Ko akan mendapat dukungan yang lebih luas dari publik,” pungkas Akhiruddin memberi saran.
Sementara terkait lingkungan hidup, Ardi dari komunitas VisTaGa, LSM Lingkungan dan Budaya di Takengon menyatakan sangat miris dengan kondisi ekosistem danau Laut Tawar saat ini.
Laut Tawar Memprihatinkan
“Kondisi Lut Tawar sudah sangat memprihatinkan. Lut Tawar sudah sakit dengan adanya kebijakan-kebijakan yang salah selama ini. Sementara obat yang diberikan sama sekali tidak tepat akibat minimnya pengetahuan teknis dari pihak terkait yang mengambil keputusan,” kata Ardi.
Karakteristik danau sudah sangat berubah, kata Ardi lebih lanjut. Hal ini akibat penebangan hutan disekitar danau, penangkapan ikan depik yang tak terkendali dan akibat masuknya limbah rumah tangga, limbah industri dan limbah pertanian ke danau. “Ikan endemik kebanggan Gayo berupa ikan Depik dan ikan Kawan akan punah,” keluh Ardi.
Amatan The Globe Journal, diskusi yang digagas Jauhari Ilyas, pemerhati seni budaya yang pernah eksis sebagai produser album Nyawoung ini diikuti sekitar tiga puluhan peserta berjalan hangat, para peserta silih berganti kemukakan pendapat.
Selain aktivis Jang-Ko, diantara yang hadir ada Mustawalad, aktivis kemanusiaan asal Gayo yang beromisili di Lhok Seumawe. Yusradi Usman al-Gayoni, penulis buku Ar. Moese. Iwan Bahagia, presiden BEM STAI Gajah Putih. Maharadi, ketua Ikatan Mahasiswa Gayo (IMAGA) Medan dan sejumlah tokoh muda lainnya dari berbagai lembaga di Gayo dan diperantauan.
Diakhir diskusi, para peserta sepakat untuk saling koordinasi untuk mendukung upaya-upaya perbaikan beberapa persoalan di Gayo dengan membangun sebuah media komunikasi memanfaatkan fasilitas internet.
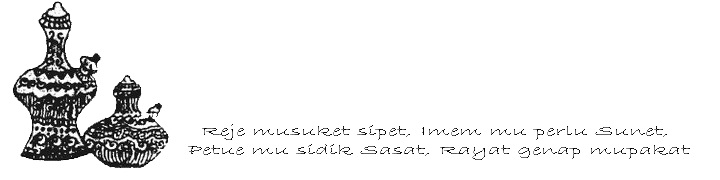

Recent Comments